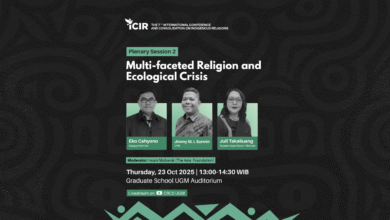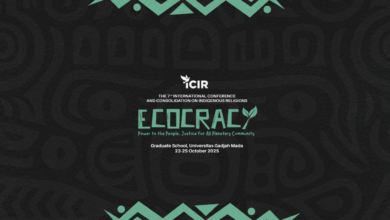Ekokrasi: Keadilan Ekologis dan Masalah Keberagaman Indonesia
Recap Plenary Session 2: “Interreligious Engagement for Ecological Justice”

Sesi pleno pertama Konferensi Internasional ICIR ke-7 mengangkat tema “Interreligious Engagement for Ecological Justice”, menghadirkan tiga pembicara lintas disiplin: Prof. Frans Wijsen dari Radboud University, Dr. Robert Setio dari Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, dan Atika Manggala dari Sri Tumuwuh, Yogyakarta.
Diskusi ini menyoroti hubungan antara iman, keadilan sosial, dan krisis ekologis yang dihadapi komunitas global, khususnya dalam konteks Indonesia. Prof. Frans Wijsen membuka sesi dengan merujuk pada ensiklik Laudato Si’ karya Paus Fransiskus yang menyerukan tanggung jawab moral umat manusia terhadap Bumi sebagai “rumah kita bersama.”
Menurut Wijsen, krisis lingkungan bukan hanya ancaman bagi alam, tetapi juga bagi keberlangsungan umat manusia, terutama generasi mendatang. “Tantangan ekologis merupakan ancaman bagi rumah bersama kita dan bagi generasi masa depan,” ujarnya.
Ia menyoroti situasi di Indonesia, di mana pembangunan nasional kerap dilakukan dengan mengorbankan rakyat miskin.
“Masyarakat adat adalah mereka yang paling dekat dengan ekologi, tetapi pada saat yang sama justru yang paling rentan terhadap eksploitasi ekologis seperti tambang dan industri ekstraktif,” tambahnya.
Robert Setio: Toward “Eco-cra(z/c)y” Interreligious Engagement for Ecological Justice
Pembicara kedua, Dr. Robert Setio, mengajak peserta untuk merefleksikan konsep ecocracy sebagai tata kelola bersama antara manusia dan Bumi.
“Ekokrasi adalah keadaan ketika bumi menjadi mitra dalam pengelolaan bersama di mana kebijaksanaan komunitas, agama, dan planet sama-sama berbicara,” tuturnya.
Ia mempertanyakan, dalam situasi sekarang, suara siapa yang benar-benar didengar, dan siapa yang terbungkam atas nama demokrasi atau ekologi.

Menurutnya, akar dari perusakan lingkungan dan konflik antaragama sama-sama berasal dari ketidakmauan untuk mendengarkan yang lain—baik manusia maupun makhluk nonmanusia.
“Jika ekokrasi itu memang punya arti, maka mestinya ini berkaitan erat dengan sikap kita untuk mendengar, sebab ini bukanlah soal berbicara tentang alam, melainkan menekankan kebersamaan dengan diam. Dari sikap seperti inilah makhluk nonmanusia mampu berbicara pada kita,” tegas Robert.
Atika Manggala: Ngalah, Ngalih, dan Ngamuk
Menutup sesi, Atika Manggala membawa perspektif kearifan lokal Jawa melalui tiga konsep kunci: ngalah, ngalih, dan ngamuk. “Ngalah adalah menghindari bencana yang lebih besar; ngalih berarti menghindari penghinaan; dan ngamuk berarti memprotes untuk menyuarakan hak dan aspirasi demi inklusi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya mentransfer nilai-nilai hidup dan spiritualitas kepada generasi muda, bukan sekadar dalam bentuk ajaran, tetapi juga melalui praktik dan kesadaran ekologis.
“Kami berusaha mentransfer apa yang kami ketahui kepada anak kami, di antaranya adalah doa dan terutama laku hidup. Dalam konteks ngamuk, kami tidak hanya menerapkan laku secara tidak tepat, melainkan dilandaskan pada kesadaran yang tepat,” jelas Atika.
Ia mengajak membangun dari dalam diri. Bersama-sama melakukan ‘laku’, dengan niat yang baik. Mulai melakukan semua kebaikan. Perkara hasil adalah kehendak Yang Maha Kuasa.
Refleksi Bersama
Sesi pleno pertama ini menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan ekologis tidak bisa dilepaskan dari dialog antariman, kebijaksanaan lokal, dan kepekaan terhadap suara-suara yang terpinggirkan—termasuk suara alam itu sendiri.
Krisis ekologis dipandang bukan hanya sebagai ancaman bagi keberlangsungan alam dan generasi mendatang, tetapi juga sebagai isu keadilan sosial yang mendesak. Prof. Frans Wijsen menyoroti ironi di Indonesia, di mana masyarakat adat yang paling dekat dengan ekologi justru menjadi yang paling rentan terhadap eksploitasi industri ekstraktif , yang sering terjadi atas nama pembangunan. Akar masalah ini, seperti ditekankan Dr. Robert Setio, adalah ketidakmauan untuk mendengarkan “yang lain”—baik sesama manusia maupun makhluk nonmanusia.
Refleksi ini mengarah pada kebutuhan untuk bergerak melampaui wacana menuju praktik nyata yang didasari spiritualitas. Dr. Robert Setio mengusulkan konsep “ekokrasi”, di mana bumi menjadi mitra dalam tata kelola bersama dan manusia harus mengambil sikap “diam” agar suara nonmanusia dapat terdengar.
Senada dengan hal itu, Atika Manggala menegaskan pentingnya mentransfer nilai dan spiritualitas melalui “laku hidup” atau praktik kesadaran ekologis kepada generasi muda. Kearifan lokal Jawa seperti ngalah, ngalih, dan ngamuk menawarkan kerangka kerja untuk bertindak, baik dalam menghindari bencana maupun memprotes secara sadar , yang semuanya harus dimulai dari niat baik dalam diri.
Kontributor: Misni Parjiati