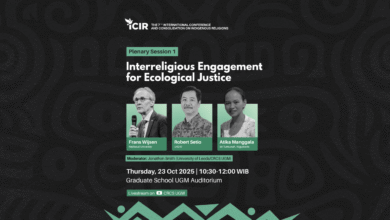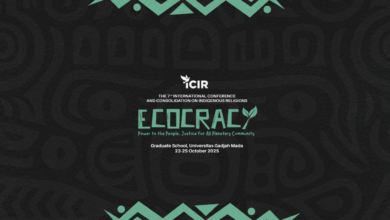Hukum dan Agama Berkhianat, Hanya Adat yang Bisa Dipercaya: Apakah Agama Selalu Ramah Lingkungan?
Recap Plenary Session 2: Multi-faceted Religion and Ecological Crisis
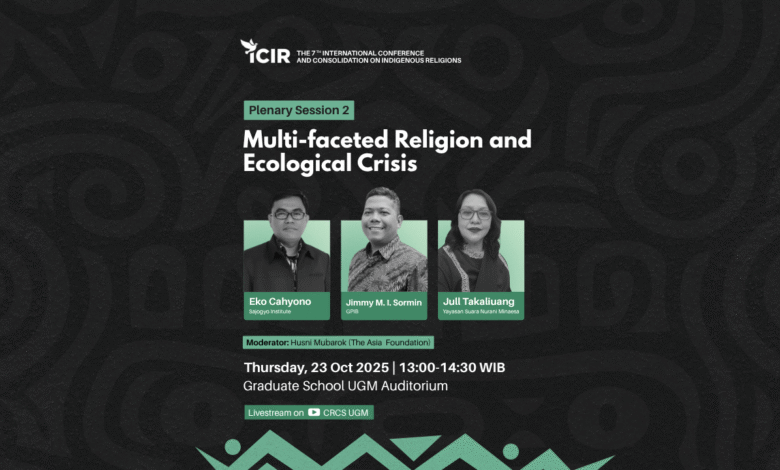
Apakah agama selalu ramah lingkungan? Agama memiliki sumber teks sebagai ajaran yang memiliki tafsir untuk memelihara lingkungan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam. Meski demikian, faktanya, kelompok agama tidak satu suara dalam merespons krisis ekologi.
Agama memiliki multiwajah—mendukung kelompok rentan yang terdampak dan menggiatkan pelestarian, sekaligus mendorong operasi proyek-proyek ekstraktif berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Topik ini menjadi pembahasan dalam plenary session kedua dari the 7th International Conference and Consolidation on Indigenous Religions (ICIR) 2025 bertajuk “Multi-faceted Religion and Ecological Crisis.”
Agama mengecewakan, kembali ke adat
Jull Takaliuang mengutarakan kondisi di kampung halamannya di Pulau Sangihe yang berada di ujung utara Indonesia dan berbatasan dengan Filipina. Nasib keadilan sosial dan ekonomi masyarakat Sangihe diabaikan pemerintah, namun baru diperhatikan saat Pemilihan Umum. Sebagai direktur Yayasan Suara Nurani Minaesa dan aktivis Save Sangihe Island, Jull menyampaikan bahwa pertambangan emas menjadi tantangan yang masih berlanjut. Padahal, Sangihe termasuk kategori pulau kecil yang harus dilindungi dari ekstraksi.
Sangihe pernah memenangkan ancaman pertambangan. Kemenangan tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat, Badan Adat Daerah Sangihe, dan otoritas agama yang menggugat sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung. Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) memberikan dua surat rekomendasi untuk menyatakan sikap teologis menolak tambang. Bahkan, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) menyurati Presiden Joko Widodo untuk mencoba membatalkan dan meninjau kembali perizinan tambang emas.
Meski demikian, tantangan pertambangan masih tersisa dan semakin masif di kawasan pesisir sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan laut. Tekanan yang dihadapi masyarakat pun semakin menjadi dengan keterlibatan aparat penegak hukum dan pemerintah setempat.
“Saya sangat sedih dan kecewa dengan gereja. Pendeta itu mesti dengar. Meskipun hanya secara hitam di atas putih akan berjuang, betul ada khotbah-khotbah untuk menyelamatkan Sangihe, tetapi dalam Sidang Sinode Istimewa GMIST pada September 2025, industri ekstraktif sebagai salah satu usaha yang dikelola untuk mendatangkan usaha bagi Badan Usaha Milik Gereja,” kata Jull. Padahal, industri ekstraktif seperti tambang logam berat telah memberikan dampak pada ekosistem, pangan, dan kesehatan masyarakat Sangihe.
“Di tengah keputusasaan kita mau bersandar ke mana? Hukum tidak ada dan agama berkhianat. Kami menemui lagi ketua adat. Apa yang kita lakukan karena hanya adat yang tidak berkhianat”. Sejak itulah masyarakat Sangihe kembali melakukan ritual adat dalumatehu sembanua demi menjaga keseimbangan alam, mencari keadilan ekologi, dan memohon perlindungan dan keselamatan.
Dinamika lembaga agama
Pendeta GPIB Jimmy M. I. Sormin tidak menampik kekecewaan Jull. Berdasarkan observasinya, ia mendapati bahwa kelompok keagamaan rentan diinstrumentalisasi oleh donor dan lembaga lain sebagai stakeholder komponen proyek daripada leading sector. Inilah yang disebut sebagai kolaborasi terbatas. Kelompok keagamaan lebih banyak menjadi objek dan penerima pelbagai proyek bantuan, alih-alih mengimplementasikan pengetahuan ekologi secara keagamaan tentang keselamatan lingkungan.
“Kolaborasi terbatas itu menyebabkan pembohongan-pembohongan, seperti yang tadi Jull katakan. Sikap gereja mendukung perlindungan lingkungan, tetapi bermain mata juga dengan pelaku bisnis ekstraktif,” kata Jimmy.
Adapun kecenderungan politik dan eksternal dari kelompok keagamaan memengaruhi respons terhadap kebijakan dan ancaman krisis ekologis. Hal tersebut membuat kelompok keagamaan bergerak untuk menjadi aktor dalam industri ekstraktif, dan bahkan meminta mendapatkan jatah pengelolaan tambang.
Jimmy memetakan titik-titik lemah internal lembaga keagamaan yang harus menjadi pembelajaran. Pertama, adanya perbedaan falsafah dan birokrasi lembaga keagamaan sehingga rantai pengambilan keputusannya membutuhkan otoritas tertinggi dengan pelbagai pertimbangan teologis dan politis.

Lalu, pelbagai lembaga keagamaan memiliki gap antar-generasi di mana kelompok muda seperti Milenial dan Gen-Z yang punya kesadaran ekologis ditempatkan sebagai generasi penerus, bukan penentu. Faktor ekonomi adalah titik lemah yang krusial karena menyangkut kebutuhan umat, namun sering kali menjadi alasan bagi lembaga keagamaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa lembaga-lembaga keagamaan tidak ada modal untuk gerakan keadilannya, sehingga bersandar pada pola ekonomi ekstraktif.
Titik lemah terakhir adalah orientasi inklusi yang terbatas. Lembaga-lembaga agama mengakui ko-eksistensial dan punya kebutuhan untuk berkolaborasi, termasuk dengan lembaga agama lainnya. Namun, inklusi ini masih terbatas untuk bekerja sama dengan agama-agama lokal, masyarakat adat, dan kelompok lainnya yang terpinggirkan. Dengan demikian, kelompok agama belum menjadi penyedia gerakan untuk “rumah bersama”.
Wajah ‘korup’ agama
“Multi-face di agama itu tidak khas,” kata Eko Cahyono dari Sajogyo Institute. Berdasarkan riset dari tahun ke tahun, Eko mengungkapkan bahwa multi-face ini ada pula di lembaga-lembaga agama lain, seperti Islam, Hindu, dan Katolik.
Pemberian jatah tambang kepada Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah salah satu contoh bagaimana Islam jatuh ke dalam industri ekstraksi. Ada pula tokoh-tokoh agama di pelbagai tempat justru menjadi aktor yang membuka akses bagi pertambangan seperti yang terjadi di Maba Sangaji. Di sisi lain, tokoh-tokoh agama Islam yang lain menolak pertambangan dan perusakan lingkungan sampai terpaksa kabur.
Kelompok Hindu Bali pun terpecah antara mendukung dan menolak rencana proyek reklamasi Teluk Benoa. Pemuka Katolik di Ende menolak geothermal, namun keuskupan Maumere melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat.
Ada banyak faktor titik lemah di selain dari yang diutarakan Jimmy, yakni perbedaan tafsir, relasi agama dan negara, relasi agama dan pemilik modal, politisasi agama, perbedaan pemaknaan situs suci, dan perbedaan makna relasi manusia dan alam. Hal tersebut, seperti yang disebut Eko, sebagai jalan akses bagi korupsi di dalam lembaga agama.
Korupsi masuk melalui pendekatan politik seperti pity corruption di mana umat muslim diumrohkan dan kristiani di bawa jalan-jalan ke Yerusalem sehingga membuka akses perizinan tambang bisa berjalan. Tokoh-tokoh agama pun menjadi pendorong “holy grabbing” di mana penggusuran dan peminggiran dibawa melalui pendekatan religius.
Oleh karenanya, ia mengkritisi bahwa ajaran hijau dalam agama atau “green deen” saja tidak cukup. “Green deen tadi mau jawab apa kalau menghadapinya sembilan haji (yang berperan penting dalam industri ekstraksi) ini? Kekuatan mereka sangat kuat,” kata Eko. Solusi hijau dalam ajaran agama belum menjawab aspek-aspek ketidakadilan ekologi.
Eko menduga ada perbedaan perspektif dalam memahami ekologi. Ia menyebut kelompok pertama menganggap krisis lingkungan hanya berkaitan dengan hal-hal kecil dengan menghadirkan solusi seperti 3R, mematikan listrik jika tidak terpakai, penggunaan tumbler, dan sebagainya. Sementara ada kelompok kedua yang lebih melihat secara struktural dalam ekonomi-politik ekologi, yakni terletak pada ketidaksetaraan relasi kuasa dan struktural. Penafsiran ajaran agama yang ramah lingkungan baru berkaitan dengan perspektif kelompok pertama, namun belum menyentuh masalah struktural yang ada dalam perspektif kelompok kedua.
Catatan penutup
Diskusi tentang sifat agama yang multifaset di Indonesia menghadirkan kontradiksi yang mendalam dalam menghadapi krisis ekologi. Sebagaimana terungkap dalam sesi tersebut, terdapat kesenjangan yang signifikan antara ajaran tekstual seperti teologi ekologi atau agama hijau dan realitas politik-ekonomi lembaga-lembaga keagamaan. Kelemahan ini berasal dari faktor internal dan eksternal.
Kelemahan internal berkaitan dengan inersia birokrasi, ketergantungan ekonomi, dan keengganan untuk memberdayakan generasi muda. Karena kelemahan internal ini, sebagaimana dicatat Jimmy, kelompok dan lembaga keagamaan menjadi pemangku kepentingan dalam “kolaborasi terbatas” untuk proyek-proyek kelompok eksternal, alih-alih menjadi pemimpin keadilan ekologis. Lembaga-lembaga keagamaan juga, pada akhirnya, “bersikap malu-malu” terhadap industri ekstraktif yang mereka lawan secara terbuka.
Kegagalan institusional ini memiliki konsekuensi yang mengerikan, terutama rasa pengkhianatan yang mendalam yang dialami oleh komunitas-komunitas rentan, seperti kelompok-kelompok adat. Misalnya, sebagaimana disaksikan Jull, setelah gereja lokal diketahui didukung oleh industri ekstraktif yang sama yang beroperasi di Kepulauan Sangihe, masyarakat merasa ditinggalkan. Sebelumnya, gereja mendukung perlawanan masyarakat terhadap penambangan emas. Setelah perubahan sikap, masyarakat memilih untuk meninggalkan pendekatan keagamaan terhadap tradisi adat.
Pada akhirnya, kontribusi konferensi berpendapat bahwa teologi “hijau” yang simplistis bukanlah respons yang memadai terhadap krisis struktural yang fundamental. Analisis Eko mengungkapkan bahwa tantangannya bukanlah menemukan interpretasi yang ramah lingkungan, melainkan menghadapi “titik akses korupsi” sistemik yang mengkooptasi tokoh-tokoh agama. Selama environmentalisme keagamaan berfokus pada tindakan individu seperti 3R, hal itu gagal mengatasi ketimpangan politik-ekonomi yang menjadi inti krisis. Oleh karena itu, agar agama dapat bertransisi dari aktor yang multifaset dan seringkali terlibat menjadi kekuatan sejati bagi ekokrasi, ia harus bergerak melampaui advokasi simplistis dan secara langsung menantang ketidakadilan struktural dan ketidakseimbangan kekuasaan yang memicu degradasi lingkungan.
Saksikan selengkapnya Plenary Session 2 dari the 7th International Conference and Consolidation on Indigenous Religion “Multi-faceted Religion and Ecological Crisis”
Kontributor: Afkar Aristoteles Mukhaer