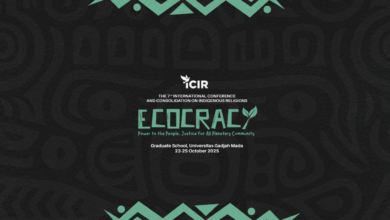Merajut Strategi Gerakan Kolektif untuk Hak Masyarakat Sipil
Recap Plenary Session 4: Collective Strategies for Protecting Civic Space and Human Rights in Indonesia

Sejak 1980an, masyarakat adat Dayak Iban Menua Sungai Utik bergerak untuk mengukuhkan wilayah ulayatnya. Inisiatif ini muncul dari kekhawatiran masyarakat adat yang berada di daerah dekat perbatasan Indonesia-Malaysia itu akan aktivitas ekstraktif seperti pertambangan dan pembalakan kayu ilegal yang dapat mengancam wilayah tempat mereka hidup.
Proses pengakuan terhadap masyarakat adat ini menghadapi jalan panjang dan berliku. Itu (it) membutuhkan kerja sama sesama warga dan dukungan dari lembaga-lembaga lain untuk menempuh proses pengakuan dari negara yang rumit. “Jangan jadi pengungsi di tanah sendiri,” kata Agustina, perwakilan warga adat Sungai Utik. “Itulah yang kemudian mendorong Apai Janggut dan tetua-tetua Sungai Utik untuk berjuang keras mendapat pengakuan wilayah adat itu. Jangan sampai saat kami meninggal nanti, meninggalkan anak cucu tanpa kepastian hukum.”
Agustina membuka diskusi bersama Zainal Abidin Bagir dari ICRS Yogyakarta, Bivitri Susanti dari STH Indonesia Jentera, dan Mochamad Mustafa dari The Asian Foundation. Diskusi ini adalah plenary session keempat bertajuk “Ecocracy in Practice: Collective Strategies for Protecting Civic Space and Human Rights in Indonesia” pada Jumat, 24 Oktober 2025. Pleno tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan the 7th Internasional Conference and Consolidation on Indigenous Religions (ICIR).
Pengakuan dan Tantangan
Setelah perjuangan sekitar 40 tahun, masyarakat adat Dayak Iban Menua Sungai Utik telah memiliki 9.480 hektare hutan adat. Pengakuan ini melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam setiap rumah panjang yang masing-masing di antaranya terdiri 28 hingga 30 keluarga. Musyawarah ini disebut sebagai beaum atau betembung di mana tetua adat seperti Apai Janggut menjadi pemimpin pertemuan tetapi tidak absolut.
“Keputusan akhir dihasilkan bukan dari pemilihan atau pemungutan suara, melainkan berasal dari dua-tiga kesimpulan. Kemudian, Tuai Rumah (pemimpin rumah panjang) akan merangkainya ke dalam keputusan akhir,” jelas Agustina. Beaum pun diselenggarakan secara inklusif dan adil dengan melibatkan laki-laki, perempuan, dan anak-anak penghuni rumah panjang dapat terlibat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, siapa saja bisa berpendapat berdasarkan pengetahuannya.
Ada pun keberhasilan masyarakat adat Sungai Utik dari musyawarah adalah mengontekstualisasikan istilah-istilah dari negara mengenai konsep kawasan konservasi. Alih-alih menggunakan istilah kawasan lindung, dan pemanfaatan terbatas, dan produksi, masyarakat menggunakan istilah lokal seperti kampung taroh, kampung galao, dan kampung endor kerja.
Meski kini telah mendapat pengakuan, bukan berarti perjuangan masyarakat Sungai Utik telah selesai. Saat ini mereka tengah menyiapkan rencana ke depan demi ketahanan komunitasnya dari pelbagai tantangan baru. Perusahaan yang dulunya memegang izin pembalakan kayu, perkebunan sawit, dan perkebunan lainnya, kini berubah menjadi pengurus karbon hijau yang dapat berdampak pada pengelolaan hutan adat. Ada pun tantangan berikutnya adalah pembangunan. Kerap kali pihak pengembang datang membawa perspektif luar yang memandang masyarakat adat membutuhkan pengembangan.
“Pertanyaannya sekarang, pembangunan untuk siapa?” tanya Agustina beretorika. “Ternyata, seperti yang disampaikan kemarin, wilayah yang banyak tambang itu justru masyarakatnya tidak sejahtera. Sementara di wilayah Sungai Utik bersama dengan enam rumah panjang di dekatnya, justru dengan mengelola sumber ekonomi kreatif secara komunal, kehidupan kita lebih berkembang [daripada mengikuti pengembang].”
Perspektif ini menjadi tantangan stigma di mana kerap kali perusahaan melihat kehidupan masyarakat adat belum berkembang. Kenyataannya, klaim Agustina, kehidupan di Sungai Utik sampai saat ini baik-baik saja. Justru konflik sosial sering terjadi di beberapa daerah di mana perusahaan ekstraktif masuk untuk beroperasi.
Kemampuan untuk berdiri di kaki sendiri ini mengantarkan masyarakat Sungai Utik dapat meningkatkan pendapatan dan tingkat pendidikan generasi mudanya. Banyak anak muda Sungai Utik berkuliah di universitas-universitas terbaik di dalam negeri dan membangun relasi yang dapat mendukung advokasi masyarakat di kampung halamannya.
Meski demikian, tantangan ke depan terletak pada generasi muda berpendidikan yang kini merantau. Warga Sungai Utik berharap mereka bisa kembali sebagai sumber kehidupan baru, menambah wawasan baru, dan peningkatan strategi dalam ketahanan masyarakat.
Strategi yang masyarakat adat Sungai Utik tidak hanya berhenti di tempatnya. Mereka melanjutkan perjuangan untuk masyarakat-masyarakat adat sekitarnya, terutama Dayak Iban Kapuas Hulu. Hal ini penting dilakukan, menurut Agustina, karena merekalah kelompok masyarakat yang mempertahankan kebudayaan Dayak dan relasi menjaga hutan yang masih tinggi.
Gerakan Rimpang
Istilah ‘gerakan rimpang’ belakangan muncul sebagai diskusi publik. Bivitri menyebut bahwa gerakan ini muncul sebagai gerakan masyarakat sipil hari ini untuk menghadapi kekuatan negara terlampau kuat. Pengurus negara (pemerintah) dan kelompok-kelompoknya ingin menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga banyak dalam praktiknya meminggirkan masyarakat akar rumput.
Demokrasi Indonesia tidak baik-baik saja. The Economist dalam analisis Intelligence Unit-nya mengungkapkan bahwa Indonesia cukup kuat secara institusi dalam kategori “functioning of government”. Namun, Bivitri memandang bahwa fungsi tersebut bukan untuk warga negara melainkan kelompok oligarki di dalam struktur kekuasaan tertinggi. Sementara DPR justru tidak tersambung dengan kepentingan rakyat.
Yang tersisa dari gerakan demokrasi adalah warga itu sendiri. Masalahnya, warga menghadapi banyak situasi yang membuat perlawanannya pun terpecah-pecah. Dia memetakan bahwa setidaknya ada empat kelompok berdasarkan konteks perlawanan, yakni:
- Aktivis. Kategori untuk kalangan yang sejak lama bergerak untuk isu demokrasi dan yang mendorong gerakan di level akar rumput seperti masyarakat adat.
- NGO, serikat buruh, dan serikat mahasiswa.
- Kelompok berbasis digital seperti influencer dan NGO berbasis digital yang biasanya adalah kelas menengah urban.
- Kolektif. Kelompok yang biasanya dibangun oleh anak-anak muda yang menolak struktur, namun skeptis dengan kerja-kerja NGO. Kelompok ini perlu dibangun dalam koneksi gerakan demokrasi alih-alih bergerak sendiri.
Permasalahannya terletak pada kekurangan dari masing-masing kelompok. Aktivis di akar rumput, aktivis lama, dan NGO, hari ini sedang menghadapi “survival mode”, terutama setelah gerakan Agustus di mana ada banyak yang ditangkap sampai saat ini. Sementara, kelompok baru berbasis digital, seperti yang menghadirkan 17+8 terbiasa dengan pikiran instan. “Padahal, kalau kita membicarakan apa yang sekarang kita hadapi, menurut saya, harus membicarakan gerakan sosial yang tidak akan dua-enam bulan selesai,” tutur Bivitri. “Kita sedang maraton, bukan sprint.”
Gerakan rimpang mengacu kelompok yang muncul di dalam masyarakat akar rumput, namun tidak terorganisasi rapi. Gerakan ini mengakar kuat dan tidak mudah diberantas, bak rimpang, namun memiliki kekurangan dalam keterhubungannya dengan kategori-kategori gerakan demokrasi lainnya. Keterhubungan ini dapat mengisi kekurangan dari kelompok lain sehingga gerakan dapat menjadi lebih kuat.
“Kalau kita sedikit-sedikit marah [untuk merespons pelanggaran demokrasi], tidak akan ada perubahan transformasi. Maka, kita perlu sekali untuk connecting the dots,” tutur Bivitri.
Senada dengan Bivitri, Mustafa memberikan kunci strategi melindungi ruang sipil terletak pada penguatan gerakan masyarakat sipil. Berdasarkan program kerja The Asia Foundation di enam kabupaten dan kota di Indonesia, Mustafa menyimpulkan bahwa penguatan ini dapat didukung dengan berkoalisi sehingga masyarakat sipil dapat memenangkan ruang-ruang kecil dalam advokasi.

“Di banyak daerah, teman-teman berkoalisi untuk mengadvokasi kebijakan. Hal tersebut bisa dilakukan, bahkan untuk isu yang sebelumnya tidak dapat dibayangkan untuk dibahas,” ujarnya. Gerakan masyarakat sipil perlu didorong untuk menciptakan semangat (vibrance) yang kemudian dapat memicu banyak pihak, termasuk kelompok rimpang yang tidak terorganisir, agar suka rela turut merespons advokasinya.
Namun, tantangan terbesarnya adalah nilai dari sebuah pekerjaan advokasi belum tentu disepakati oleh kebanyakan orang. “Maka, dalam menjalankan kegiatan, persoalannya adalah kita mewakili kepentingan siapa? Lawan kita bisa berbeda-beda. Inilah strategi yang harus dibicarakan,” kata Mustafa. Dalam pengertian tersebut, advokasi memerlukan kesamaan nilai dengan komunitas-komunitas lainnya di akar rumput sehingga dapat menjadi kekuatan bersama dalam membangun gerakan masyarakat sipil.
Dalam menyambungkan pelbagai elemen, tidak dapat dipungkiri bahwa melibatkan elite pun diperlukan. Bivitri memberikan contoh bahwa keterlibatan elite dalam gerakan pernah berhasil ketika menurunkan Suharto dari kekuasaan. Saat itu, kondisi elite tengah mengalami keretakan. Sayangnya, gerakan hari ini tidak punya sekutu yang dapat membantu dorongan secara transformatif.
Menurut Mustafa, memasukkan kelompok elite dalam pemerintahan memberikan keuntungan berupa perlindungan untuk gerakan, setidaknya dalam advokasi di daerah. Setiap tempat punya strateginya sendiri untuk mencari dan membangun koalisi bersama elite lokal. Mustafa berpendapat bahwa koalisi seperti ini tidak hanya sekadar strategi, melainkan menciptakan konsensus perubahan yang sering kali tidak dapat dilakukan dalam advokasi biasa.
“Sayangnya, kolaborasi dengan pemerintah sering ada simalakama ketika berhadapan dengan isu-isu yang dapat berubah. Jadi, harus berhati-hati dalam kolaborasi dengan pemerintah,” lanjutnya. Gerakan masyarakat sipil yang ingin membangun kolaborasi dalam koalisi ini memerlukan perspektif kritis dari setiap kebijakan yang dihasilkan.
Oleh karenanya, Bivitri juga menyarankan agar membangun gerakan warga tidak terhenti pada gerakan moral atau survival. Gerakan demokrasi harus mengarah sebagai gerakan politik. Sebagai menambal kekuatan-kekuatan yang masih kurang dalam pergerakan, adalah hal yang penting untuk memperbanyak “blok-blok politik” yang mendorong pendidikan warga menyelesaikan permasalahan politik sehari-hari.
Advokasi Interseksional
Zainal Abidin Bagir menawarkan advokasi interseksional untuk mendorong pergeseran atau memperkaya strategi, khususnya dalam hukum seperti litigasi. Salah satu elemen yang dapat membantu penguatan HAM dan demokrasi itu adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Menurutnya, pengembangan KBB di Indonesia mengalami perkembangan pesat sepanjang 20 tahun terakhir.
Pada 2000, amandemen kedua UUD 1945 memasukkan bab tentang HAM. Sejak itu pula, kebebasan beragama atau berkeyakinan menjadi salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan hak-hak warga lainnya di Indonesia.
Zainal membagi 20 tahun advokasi KBB menjadi dua: 10 tahun pertama dan kedua. Pada sepuluh tahun pertama, fokusnya KBB baru diperkenalkan dengan pengaruh kebebasan HAM pasca-reformasi yang ambigu. Masa ini menghadirkan keragaman kelompok beragama yang bergerak bebas. Isu keagamaan pun mulai masuk di dalam ranah pengadilan. Babak kedua adalah periode kepresidenan Joko Widodo di mana politik keagamaan menjadi toksik. Pada masa ini, strategi represi dipakai kepada kelompok-kelompok agama yang banyak tidak disukai orang dan memberikan akomodasi kepada kelompok agama yang dianggap moderat dan menguntungkan.
“Ini adalah yang disebut repressive pluralism,” kata Zainal. “Seakan pluralis dengan membesarkan kelompok pluralis dan toleran, tetapi melakukan represi [kepada kelompok beragama oposan].” Represivitas ini melibatkan pembubaran dan pembunuhan oposan. Sementara kelompok yang dianggap moderat diberi hadiah finansial yang puncaknya adalah pemberian konsesi tambang untuk organisasi keagamaan.
Namun, di satu sisi, sepuluh tahun kedua mendorong pada inklusivitas KBB, walaupun masih menjadi bagian dari repressive pluralism itu sendiri. Kementerian Agama menjadi salah satu aktornya yang memperkenalkan moderasi beragama sebagai flagship. Sayangnya, KBB ini masih stagnan karena masalah lama terus berlangsung tanpa penyelesaian. Zainal menyebutnya sebagai “kemajuan setengah hati” karena masih ada beberapa pendekatan yang gagal seperti menyelesaikan hukum pidana tentang penodaan agama, masalah rumah ibadah, dan pengakuan agama adat.
Advokasi KBB hari ini semestinya, menurut Zainal, dapat berkembang dalam kesalingketerkaitan dengan hak-hak lainnya dalam prinsip utama HAM. Advokasi KBB belakangan mulai menjurus dengan keterlibatan pihak-pihak yang tidak semuanya berfokus pada KBB itu sendiri, melainkan isu lainnya.
“Satu hal yang dirasakan kelemahan dalam aktivisme KBB adalah tidak terhubung dengan aktivisme dalam bingkai besar demokrasi. Ada yang anggap hal ini enggak penting, ada yang anggap KBB enggak penting dengan isu korupsi, lingkungan, dan sebagainya,” ujarnya. “Padahal, semuanya terhubung kalau dilihat dari metodologi interseksionalitas.”
Dia memberikan contoh bagaimana advokasi KBB adalah bagian dari interseksionalitas dalam isu lingkungan dan masyarakat adat. Selama ini LSM memandang bahwa perjuangan masyarakat adat hanya berkaitan dengan tanah. Padahal, rekognisi terhadap tanah yang merupakan tempat-tempat sakral harusnya berjalan dengan rekognisi terhadap tradisi dan kepercayaan mereka secara bersama. “Tidak bisa rekognisi tanah tanpa rekognisi tradisi. Sebaliknya, tidak bisa rekognisi tradisi tanpa rekognisi hutannya,” terang Zainal.
Namun, pekerjaan untuk menggabungkan titik-titik perspektif mengenai suatu isu dalam masyarakat sipil ke dalam interseksionalitas bukanlah perkara mudah. Menurut Mustafa, menggunakan pendekatan interseksionalitas tidak dapat dipakai dalam setiap situasi. Berdasarkan pengalamannya, menggunakan pendekatan ini tanpa kehati-hatian dapat menjadi suatu isu yang diadvokasi dapat melebar dan tidak terselesaikan.
“Yang pasti bisa, dan ini efektif, adalah jika interseksionalitas itu adalah pada aktor-aktornya. [Membangun] koalisi menjadi interseksional, terdiri dari aktor yang berbeda-beda lebih mudah dipraktikkan ketimbang menurut perspektif-perspektifnya,” tutur Mustafa.
Kesimpulan: Memintal Benang Merah Strategi Gerakan Kolektif
Sebagai kesimpulan, perjuangan masyarakat sipil untuk mempertahankan haknya sebagai warga negara menghadapi tantangan berat, mulai dari ancaman ekstraktif di tingkat akar rumput, negara yang cenderung melayani kelompok oligarki, hingga fragmentasi dalam gerakan masyarakat sipil itu sendiri. Benang merah utama dari seluruh diskusi adalah urgensi untuk meninggalkan pola kerja advokasi yang terisolasi. Langkah penguatan isu HAM dan masyarakat sipil menuntut adanya strategi yang berfokus pada pembangunan konektivitas, koalisi, dan perjuangan jangka panjang sebagai langkah ke depan.
Strategi konektivitas ini dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Bivitri Susanti menyoroti pentingnya “menyambungkan titik-titik” antar kelompok gerakan yang terfragmentasi untuk mengisi celah dan memperkuat gerakan “rimpang” yang berakar kuat namun kurang terhubung. Secara strategis, Mochamad Mustafa menambahkan pentingnya membangun koalisi untuk memenangkan ruang-ruang advokasi kecil , yang didasari oleh kesamaan nilai di tingkat akar rumput dan kolaborasi kritis dengan elite atau pemerintah. Selain menghubungkan aktor, Zainal Abidin Bagir menekankan perlunya “advokasi interseksional” yang menghubungkan berbagai isu, seperti mengaitkan perjuangan pengakuan tanah adat (isu lingkungan) dengan pengakuan tradisi dan kepercayaan (isu KBB).
Kisah sukses masyarakat adat Sungai Utik, yang dipaparkan oleh Agustina, menjadi bukti nyata dari kekuatan strategi kolektif. Perjuangan mereka selama 40 tahun untuk mendapatkan pengakuan hutan adat didasari oleh musyawarah beaum yang inklusif dan menghubungkan seluruh elemen komunitas. Keberhasilan ini mengajarkan bahwa perjuangan advokasi, seperti yang Bivitri analogikan, adalah sebuah “maraton” yang membutuhkan ketahanan yang berkelanjutan, alih-alih “sprint” yang mengejar kecepatan. Oleh karena itu, gerakan demokrasi ke depan tidak boleh berhenti sebagai gerakan moral atau survival , melainkan harus diarahkan menjadi gerakan politik yang membangun “blok-blok politik” untuk pengembangan kapasitas warga. Melalui pembangunan koalisi aktor yang interseksional dan berbagi nilai, gerakan masyarakat sipil dapat membangun kekuatan bersama yang lebih solid.
Saksikan selengkapnya Plenary Session 3 dari the 7th International Conference and Consolidation on Indigenous Religion “Collective Strategies for Protecting Civic Space and Human Rights in Indonesia.”
Kontributor: Afkar Aristoteles Mukhaer